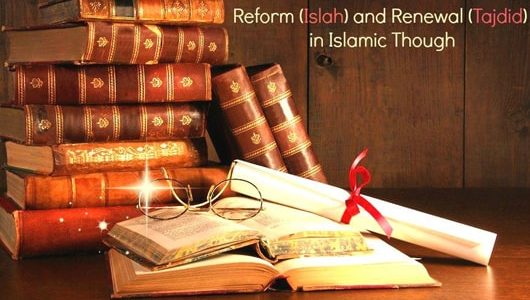Oleh: Alimuddin Hassan Palawa,
Pada galibnya, lahirnya kesadaran iṣlāḥ (reformasi [perubahan kearah perbaikan]) dan munculnya semangat tajdīd (pembaharuan) dalam Islam dipicu setelah lahirnya modernism di Dunia Barat. Menurut Nurcholish Madjid, ada dua peristiwa yang sangat menentukan menandai dimulaianya Abad Modern yang terjadi pada sekitar pertengahan abad ke-18.
Pertama, Revolusi Industri yang ditandai dengan kecanggihan “teknikalisme” dengan tuntutan efesiensi kerja yang tinggi diterapkan dalam semua bidang kehidupan. Kedua, Revolusi Perancis yang ditandai dengan pembebasan “kemanusiaan” atas tatanan sosial budaya dan politik yang sudah dipandang “usang” dan “membusuk”. Nurcholish Madjid menambahkan bahwa modernisme lahir tidak pada wilayah Eropa yang mempunyai masa lampau yang panjang dan gemilang, yaitu Yunani dan Romawi, melainkan di Inggris dan Perancis di Eropa Barat Laut yang merupakan pendatang baru dalam pentas sejarah umat manusia.
Kelak, ternyata aspek kemanusiaan yang tercermin dalam cita-cita Revolusi Perancis lebih bermakna daripada Revolusi Industri yang terwujud dalam teknikaliasi yang canggih sekalipun. Maka sering pula disebutkan tentang peranan utama “generasi revolusi Prancis 1789” dalam meletakkan dasar-dasar Abad Modern itu (Nurcholish Madjid, Kahazanah Intelektual Muslim, 50).
Berat dugaan, lantaran arti penting yang dikandung dalam tahun “1789” itu, sehingga Albert Hourani “berhijtihad” menetapkan tahun 1789 sebagai awal mula munculnya Era Liberal. “Ijtihad” Hourani ini, menurut Luthfi Assyaukanie, merupakan salah satu sumbangannya dalam memberikan patokan, belakangan diikuti oleh hampir semua sejarahwan, dalam memulai penulisan kesejarahan pemikiran Arab-Islam.
Tahun 1789 adalah tahun dimana Napoleon Bonaperta beserta pasukannya menginjakkan kakinya di Mesir. Hourani meyakini bahwa sejarah pemikiran Arab Modern atau sejarah Era Liberal bagi masyarakat Arab, bukan dimulai dari Muhammad ibn Abd Wahhab (1701-1893) di Arab Saudi. Lihat, Luthfi Assyaukanie “Pengantar”, dalam Albert Hourani, Pemikiran Liberal Dunia Arab, Bandung: Mizan, 2004), hal. xvii.
Abad Modern yang lahir di Barat itu merupakan kelanjutan logis dari peradaban yang telah dibina oleh umat Islam selama berabad-abad. Akan tetapi, justru umat Islam pulalah yang paling menderita menghadapinya. Menurut Nurcholish Madjid, ini dapat diterangkan paling tidak tiga argumentasi.
Pertama, dari segi psikologis, karena perasaan sebagai kelompok manusia paling unggul selama ini, umat Islam tidak mempunyai kesiapan mental sama sekali untuk menerima kenyataan bahwa bangsa non-Islam bisa lebih maju dari mereka.
Kedua, sejarah interaksi permusuhan yang lama antara Dunia Islam dengan Dunia Kristen (Barat). Orang-orang Eropa tetap menyimpan dendam untuk menaklukan Spanyol di Barat dan negeri-negeri Balkan di Timur. Selain itu, permusuhan antara keduanya yang berkempanjangan dalam Perang Salib dengan kekalahan tentara Kristen.
Ketiga, letak geografis Dunia Islam yang berdampingan serta bersambungan dengan Eropa, yang memperbesar kedua argumen sebelumnya. (Lihat, Nurcholish Madjid, Kahazanah Intelektual Muslim, 54-55).
Misi dagang Eropa abad keenam belas dan tujuh belas secara progresif meluas hingga sejak abad ke-18 banyak dari wilayah dunia Muslim merasakan dampak ancaman ekonomi dan militer dari teknologi dan modernisasi Eropa. Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20 Bangsa Eropa, khususnya Inggris, Prancis dan Belanda semakin masuk dan mendominasi sejumlah wilayah Dunia Muslim, mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara. (John L. Esposito, Islam the Staight Path, (New York: Oxford University Press, 1991: 124)
Dominasi Dunia Eropa atas Dunia Islam, diakui atau tidak, sejatinya, meskipun dalam “wujud rupa” yang berbeda masih berlangsung hingga dewasa ini, misalnya hegemoni dan “pendiktean” budaya yang dilakukan oleh Barat-Eropa atas Timur-Islam. Misalnya, cara pandang orang-orang Barat-Eropa sangat menghegemoni dalam mempengaruhi dan menentukan cara pandang orang-orang Timur (Islam) bukan saja dalam melihat sejarah dunia, tetapi juga dalam melihat “dirinya sendiri” dalam perjalanan sejarahnya.
Hasan Hanafi, misalnya, menyatakan bahwa term “Timur Tengah” adalah berasal dari bahasa Inggris, ciptaan dan cara pandang Barat terhadap Timur (Dunia Islam khususnya.) Negara-negara Arab yang saat ini dikenal dengan “Timur Tengah” karena dibandingkan dengan negara-negara Arab kawasan Barat, seperti Maroko (dan sekitarnya) yang disebut dengan “Timur Dekat; atau dibandingkan dengan Cina yang berada di “Timur Jauh” bagi (cara pandang) orang Inggris. Lihat, Hasan Hanafi, “Pengantar” dalam Aunul Abied Shah, Muhammad, et al., Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Bandung: Mizan, 2001), 21.
Belakangan, pendapat sama dinyatakan oleh Tamin Ansary, katanya: “…. frase Timut Tengah mengasumsikan sesorang sedang berdiri di Eropa Barat –jika anda berdiri di dataran tinggi Persia, misalnya, yang disebut Timur Tengah itu sebenarnya adalah Barat Tengah. Oleh karena itu, saya lebih suka menyebut seluruh wilayah dari Indus hingga Istambul ini Dunia Tengah, karena ia terletak di antara dunia Mediterania dan dunia Cina.” Tamim Ansary, Dari Puncak Baghdad Sejarah Dunia Versi Islam (Jakarta: Zaman, 2009), 30.
Untuk itu, menurut Hasan Hanafi, sudah saatnya Dunia Timur (orient), khususnya Dunia Islam, “membalikkan keadaan” untuk tidak lagi melulu “dipandang” (menjadi objek kajian) oleh Dunia Barat (oksident) sebagai subjek, tetapi justru Dunia Timur (Islam) harus menjadi “subjek” oksidentalisme dalam “memandang” Dunia Barat. Dengan bahasa singkat, masa lalu dunia Islam di baca dunia Barat, masa datang dunia Islam membaca dunia Barat. Lihat Hasan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat, (Jakarta: Paramadina, 1999), 25-33.
Dengan pendekatan oksidentalisme ini, menurut Komaruddin Hidayat, Hasan Hanafi bermaksud “mendobrak dan mengakhiri mitos Barat sebagai representasi dan pemegang supermasi dunia”, khususnya dalam kajian keilmuan. Dan sekaligus bertujuan “pembebesan diri dari pengaruh pihak lain agar terdapat kesetaraan antaran al-āna yakni dunia Islam dan Timur pada umumnya, dan al-ākhar yakni dunia Eropa dan Barat pada umumnya. (Lihat, Hidayat, “Oksidentalisme: Dekonstruksi Terhadap Barat”, dalam Hasan Hanafi, Oksidentalisme: Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat, (Jakarta: Paramadina, 1999), xix.
Munculnya perenungan, respon dan otokritik dikalangan para pembaharu pemikiran Islam dengan melakukan upaya iṣlāḥ dan tajdīd, tidak dapat dipungkiri, berjalin kelindangan dengan dominasi Dunia Eropa atas Dunia Islam, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Meskipun demikian, tanpa bermaksud melakukan “apologia atas ketidakberdayaan”, konsep reformasi (iṣlāḥ) dan pembaharuan (tajdīd), sejatinya adalah komponen yang fundamental dalam ajaran Islam yang berakar dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.
Mengenai konsep reformasi (iṣlāḥ) dan pembaharuan (tajdīd), Lihat, Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, dalam P. M. Holt, Ann K. S. Lambton and Bernard Lewis, The Cambridge History of Islam, New York: Cambridge University Press, 1970, hal. 632-642). Kedua konsep itu, menurut Jhon L. Esposito, mengadung seruan untuk kembali kepada sumber utama Islam: Al-Qur’an dan al-Sunnah. (John L. Esposito, Islam the Staight Path: 115).
Konsep iṣlāḥ dalam pengertian kebenaran moral yang kuat maupun membentuk kembali, semata-mata demi memperbaiki perbuatan, bertalian langsung dengan tugas panjang risalah al-nubuwwah. Nabi Sya‘ib umpanya, bercerita kepada umatnya: “Saya hanyalah menginginkan islah pada batas-batas kekuasaan saya.” Mereka yang melakukan iṣlāḥ, sering dipuji dalam al-Qur’an, dan mereka dilukiskan sebagai pelaksana perintah Allah.
Dengan cara pandang semacam itu, walaupun nabi-nabi telah berakhir dan upaya iṣlāḥ mereka sudah berakhir, namun pekerjaan iṣlāḥ sebagai sebuah risalah kenabian, yaitu perubahan kearah perbaikan, berlangsung terus sebagai bagian dari tanggungjawab seorang beriman. (John O. Voll, “Pembaharuan dan Perubahan Dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah” dalam John L. Esposito, Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan, (Jakarta: Rajawali Press, 1987: 22-23).
Konsep tajdīd dalam Islam didasarkan pada hadis Nabi: “Tuhan akan mengirim untuk umat ini, pada awal setiap abad, mereka yang akan memperbaharui agama ini.” Sang pembaru (mujaddid) Islam diyakini akan dikirim Tuhan diawal setiap abadnya untuk mengembalikan pelaksanaan ajaran yang sejati. Mengingat regenarasi umat dalam sepanjang sejarah cenderung menyimpang dari jalan yang lurus. Ada dua aspek utama dalam proses ini, yaitu (i) kembali pada pola ideal sebagaimana termaktup dalam al-Qur’an dan al-Sunnah; dan (ii) hak untuk berijtihad, dan untuk menafsirkan sumber-sumber Islam. (Lihat, John L. Esposito, Islam the Staight Path: 116; John O. Voll “Pembaharuan dan Perubahan Dalam Sejarah Islam: 23).
Dalam melakukan reformasi (iṣlāḥ) dan pembaharuan (tajdīd) dengan mencermati problem-problem dihadapi dunia Islam, di kalangan intelektual dan pemikir pembaharu Muslim terdapat beberapa variasi pandangan dan pemikiran sebab-sebab keterbelakangan kaum Muslim dan sekaligus upaya solusi pemecahannya.
Pertama, pemikir kelompok Muslim yang melihat bahwa biang keladi seluruh keterbelakangan dunia Islam adalah kerena berkembangnya paham khurafat dan telah menjauhnya kaum Muslim dari ajaran aslinya, al-Qur’an dan Hadis. Menurut kelompok ini, jika umat Islam ingin meraih kembali kejayaan masa silam yang pernah dimiliki, mereka harus kembali ke pangkal; mengikis segala khurafat dan bid’ah serta kembali kepada al-qur’an dan al-Sunnah. Dalam kelompok ini dimotori oleh Muhammad ibn Abd Wahab dan belakangan menjadi gerakan Wahabisme yang dikenal sebagai gerakan furifikasi dalam Islam. (Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, (Jakarata: Bulan Bintang, 1975: 23-26).
Kedua, kelompok pemikir Muslim yang melihat bahwa sebab-sebab ketidakberdayan dunia Islam tersebut dikarenakan perpecahan dan tidak adanya persatuan di kalangan umat Islam yang mengakibatkan mereka menjadi terjajah. Untuk itu, menurut kelompok ini, umat Islam harus menggalang persatuan dan membebaskan diri belenggu penjajahan. Dalam kelompok ini termasuk Jamaluddin al-Afghani sebagai pelopor utamanya; yang terkenal dengan pemikirannya tentang Pan-Isalamisme. (H.A.R. Gibb, Aliran-Aliran Modern Dalam Islam, [terj. Machnun Husein] (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 49; Albert Hourani, Pemikiran Liberal Dunia Arab, (Bandung: Mizan, 2004: 186-187).
Ketiga, kelompok pemikir Muslim yang melihat bahwa biang kerok dari segala keterbelakangan dunia Islam adalah karena kejumudan pemikiran lantaran tertutupnya pintu ijtihad. Sebagai jalan keluarnya agar ummat Islam dapat kembali membangun peradabanaya, mereka harus membuka lebar-lebar pintu ijtihad dengan mempergunakan rasionalitas-liberalitas secara kental, sembari mengambil nilai-nilai dari barat yang relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam.
Di antara tokoh dari kelompok terakhir ini sangat artikulatif adalah Muhammad Abduh yang sengat masyhur dengan rasionalismenya. (Pembahasan panjang lebar prihal Muhammad Abduh dan pemikirannya, lihat Charles C. Adam, Islam and Modernism in Egypt: A Study of the Moderen Reform Movement Inaugurated by Muhammad Abduh, London, New York: Russell & Russell, 1968). Untuk melihat rasionalitas Muhammad Abduh, lihat Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah, (Jakarta: UI Press, 1987: 43-57) .
Wa Allāh a‘lam bi al-Ṣawāb
Mā tawfīq wa al-Hidāyah illa bi Allāh
(Peneliti ISAIS [Institute for Southeast Asian Islamic Studies] UIN Suska Riau)