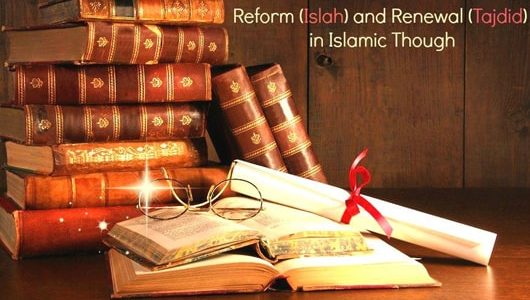Oleh Alimuddin Hassan
Raja Ali Haji sendiri memberikan arti ḥasd menjadi dengki dengan pengertian, yaitu: “suka seorang akan hilang nikmat yang lainya, sama ada pada nikmat dunia atau nikmat agama.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 54). Di dalam al-Qur’an ditemukan pengertian ḥasd (dengki) dengan sangat jelas: “Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya.” (Q.S. Āli Imrān [3]: 120).
Kalau sekiranya sifat dengki yang bersemayam dalam hati itu mampu diredam dengan segala daya upaya, sehingga tidak sempat diaktulisasikan, tentu tidak akan menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa telah berkata seorang pria kepada Hasan Basri, “apakah seeorang mukmin itu bisa mendengki?” Ia berkata, “Apakah kamu ingat pada anak-anak Ya‘qub (kisah Nabi Yusuf as)?” Ia menjawab, “Ya”. Hasan Basri berkata, “Ada kesusahan (kedengkian) di dadamu. Namun itu tidak akan membahayakanmu, selama kamu tidak mengeluarkannya melalui tangan dan lidah.” Lihat, Muslih Muhammad, Kecerdasan Emosi Menurut al-Qur’an [terj. Emiel Threeska] (Jakarta: Zaituna, 2010), 130.
Meskipun demikian, dengki semacam ini belum/tidak bisa dikategorika sebagai dengki yang “postif”. Yang dimaksud “dengki positif” adalah “dengki” pada seseorang yang senantiasa berbuat baik dan berupaya untuk menandingi kebaikan orang bersangutan. Dalam konteks ini, sebagaimana sabda Nabi saw., hanya dua dengki yang dapat dibenarkan, sebagaimana sabda Nabi saw.: “Jika dengki (iri hati) bisa dibenarkan, maka hanya ada dua orang yang boleh menjadi obyek paling tepat bagi kedengkian. Pertama, kepada orang seseorang yang diberi rezki oleh Allah dan dianugrahi kekuatan untuk senantiasa mengeluarkannya buat keadilan. Kedua, kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan oleh Allah dan beramal sesuai dengan ilmunya, dan terus memberikan (mengajarkan) ilmunya kepada orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim, berdasarkan keterangan Ibn Mas‘ud).
Akan tetapi, kalau sifat dengki tersebut dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan, maka intelektual Melayu-Riau ini menyebutkannya, “bernama dengki yang jahat lagi dosa besar.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 54). Dengki yang disebut belakangan tidak bisa ditolerir, sehingga Raja Ali Haji menambahkan dengan kalimat yang tegas, “Inilah orang yang celaka bedebah, yang didapatkan juga balas kejahatan itu di dunia, di dalam akhirat.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 54).
Dengki termasuk dosa besar ketiga yang mula-mula dilakukan oleh makhluk Allah. Pertama, kesombongan yang dilakukan oleh Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, sehingga menyebabkannya menjadi makhluk Allah yang (paling) terkutuk. Kedua, kerakusan Adam (dan hawa) yang, meskipun telah dilarang Allah, memakan buah pohon “terlarang”, sehingga menyebabkannya terusir dari surga dan/ terbuang di bumi. Ketiga, kedengkian Qabil kepada Habil, sehingga Qabil membunuh saudaranya itu. Dengki yang disebut belakangan tidak bisa ditolerir, sehingga Raja Ali Haji menambahkan dengan kalimat yang tegas, “Inilah orang yang celaka bedebah, yang didapatkan juga balas kejahatan itu di dunia, di dalam akhirat.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 54.
Sifat dan perbuatan dengki mempunyai akibat tidak saja pada diri orang yang bersangkutan, tetapi lebih-lebih pada orang lain, seperti ungkapan Raja Ali Haji sendiri, “dengki itu membawa kebinasaan dirinya, hingga sampai membinasakan orang yang lainnya. Na‘uzu bi Allah.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 55). Untuk diri orang bersangkutan, apabila sifat dengki sudah mengkristal maka akan mengakibatkan sejumlah keburukan dan kehinaan pada dirinya. Dalam Gurindam Duabelas Raja Ali Haji bertutur:
Apabila dengki sudah tertanah
Datanglah daripadanya beberapa anak panah.
Ada beberapa “anak panah” sebagai akibat dan bahaya yang akan ditimpakan kepada orang-orang dengki. Pertama, orang dengki akan dimusnahkan amal ibadahnya di akhirat kelak. Artinya, pahala amal ibadah si-pendengki di dunia ini habis “dimakan” oleh kedengkiannya dengan sangat mudah, laksana api memakin kayu bakar yang kering. Rasulullah saw. bersabda: “iyyākum wa al-ḥasad inna al-ḥasad ya’kul al-ḥasanah kamā ta’kul al-nār al-khaṭab.”(Jauhilah olehmu semua kedengkian, karena kedengkian itu memakan segala kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar yang kering). [HR. Abu Daud]).
Kedua, orang dengki akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, kemungkaran dan kemaksiatan, seperti berbohong, mengumpat, mencaci-maki, berseteru dengan orang lain, dan bahkan sampai saling membunuh.
Ketiga, orang dengki, menurut Raja Ali Haji, tidak akan mendapat shafa’at dari Nabi Muhammadsaw. di akhirat. Karena orang pendenki bukan bagian dari ummat Nabi Muhammad saw., sebagaimna sabdanya: “man ḥasada laysa minnā ” (orang yang dengki itu bukan daripada aku).
Keempat, orang dengki itu, langsung atau tidak langsung, telah berburuk sangka, menyalahkan dan marah kepada Allah atas anugerahkan nikmat yang diberikan kepada orang lain. Dengan sendirinya dapat dipastikan bahwa orang dengki semacam tidak akan pernah persyukur pada Allah dan sekaligus ingkar (kufur) atas nikmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu, menurut Raja Ali Haji, orang dengki tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak.
Kelima, orang dengki akan membawa mudarat kepada orang yang didengkinya, seperti melancarkan fitnah. Untuk itu, Rasulullah berlindung kepada orang pendeki, sebagaimana berlindung kepada syaithan. Dalam al-Qur’an ada perintah kepada Muhammad saw. agar memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai cuaca pagi/subuh (rabb al-falāk) dari kejahatan seorang pendengki apabila mendengki (wa min sharri ḥāsd ithā ḥasd . Q.s. al-Falak [113]: 5).
Keenam, orang dengki senantiasa hatinya merasa menderita dan berduka cita melihat orang didengkinya semakin sukses, dan senantiasa berharap dan berusaha sekuat mungkin agar orang yang didengkinya itu gagal dan menderita. Dengki semacam ini adalah pangkal kesengsaraan orang bersangkutan. Semakin yang didengkinya itu tampak “bahagia” [kata bahagia ini beri tanda petik karena sejatinya yang orang didengkinya itu benar-benar bahagia] maka ia semakin menderita. Orang pendengki dengan sendirinya akan selalu gelisah dan tidak bahagia, karena ia selalu dihantui perasaan takut dikalahkan oleh orang lain.
Ketujuh, orang dengki itu akan dibutakan mata hatinya oleh Allah, sehingga dia tidak kebenaran dan kebaikan serta tidak mampu lagi melihat kebmengerti akan hukum-hukum Allah. Menyebab itu semua, menueur Raja Ali Haji, lantaran hatinya selalu digerogoti sikap dengki kepada orang lain.
Delapan, orang dengki itu dibenci Allah, sehingga Allah tidak akan ditolong mereka dalam menjatuhkan/membinasakan musuh-musuhnya. Apa lagi, orang yang didengkinya itu terkadang dizaliminya, sehingga Allah berpihak dan mengasihi hamba-hamba-Nya yang dizalami itu. Akhirnya, Raja Ali Haji menyatakan bahwa penguasa dan pembesaran kerajaan harus mencermati akibat dan bahaya yang akan ditimbulkan oleh sifat dengki dengan mengacu pada al-Qur’an dan Hadith serta karya-karya ulama belakangan (mutakhkhirīn) dan ulama terdahulu (mutaqaddimīn). (Lihat, Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 54-56).
Ḥasd (dengki) merupakan salah satu sifat negatif yang bersemayam dalam hati. Karena hati secara individual adalah “raja” yang ada dalam anggota tubuh manusia, maka hati harus disucikan dari sifat hasad. Begitu pula, karena “raja” secara sosiologis adalah “hati” yang ada dalam anggota masyarakat, maka sifat hasad tersebut harus dihilangkan dari seorang raja. Untuk itu, dengki adalah termasuk sifat paling tercela dan “najis”. Raja Ali Haji menyatakan bahwa sifat dengki harus ditinggalkan penguasa dan pembesar karena kalau tidak bisa menyebabkan kebinasaan bagi kerajaan dan masyarakat.
“Seyogyanya hendaklah raja-raja dan segala orang besar-besar menjahukan penyakit najis berdengki-dengkian itu karena apabila banyaklah dan zahirlah di dalam suatu negeri akan ahlinya banyak berdengki-dengkian alamat negeri itu akan binasa jua akhirnya. Apalagi orang besarnya berdengki-dengkian mangkin segeralah binasanya. Maka hendaklah raja itu baik-baik benar siasat kepada kaum kerabatanya dan kepada menterinya hulubalangnya yang berdengki-dengkian itu.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 58-59).
Seorang penguasa (raja) seyogyanya cepat tanggap dalam menyelesaikan pertikaian akibat dari sikap dan prilaku dengki di kalangan pembesar kerajaan. Akan tetapi, setelah diambil langkah-langkah “bijak” [baca: dipujuk dan disuluhkan] ternyata pembesar kerajaan tetap tidak juga berubah, maka penguasa (raja) harus mengambil langkah dan sikap tegas, yaitu “maka dilepaskanlah ia daripada jabatannya atau dienyahkan daripada negeri…”
Sekiranya penguasa (raja) tidak mengambil langkah-langkah pencegahan tertentu, maka sikap dengki di kalangan pembesar kerajaan dapat saja memicu dan menular kepada masyarakat. Akibatnya, penguasa sendiri yang menjadi susah dalam menyelesaikan pengaduan di kalangan masyarakat yang bertikai. Konsekwensi selanjutnya, kalau pertikaian itu tersebut tidak ditangani dengan baik, menurut Raja Ali Haji, akan dapat memicu terjadinya kegaduhan, yaitu “berpukul-pukulan dan berbunuh-bunuhan” yang dapat mengancam keselamatan negeri, “… inilah kebinasaan dan kerusakan apabila banyak isi negeri itu berdengki-dengkian.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 58-59).
Ungkapan-ungkapan Raja Ali Haji di atas dapat diduga kuat terilhami dari sabda-sabda Nabi saw, seperti sabda Rasul Allah: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasul Allah saw. bersabda: “Akan menimpa umatku racun umat-umat lain.” Para sahabat bertanya, “Apa itu racun umat-umat lain?”. Rasul Allah saw. bersabda: “Bersenang-senang tanpa batas, sombong, memperbanyak harta, berlomba hidup duniawi, saling menjauh, saling dengki, hingga terjadi pembangkangan, kemudian kekacauan.” (HR. Tabrani). Dalam Riwayat lain, Rasul Allah bersabda: “Yang paling kutakutkan pada umatku adalah memperbanyak harta. Lalu mereka saling mendengki dan saling membunuh.” (HR. Al-Hakim).
Untuk mengobati penyakit dengki, menurut Raja Ali Haji, secara umum ada dua: ilmu dan amal. Dengan ilmu kita akan mengetahui bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh sifat dengki, sebagiamana disebutkan di atas. Dengan amal kita hendaknya jangan sampai mengejawantahkan sifat dengki itu dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, Raja Ali Haji mengutarakan agak terperinci bagaimana cara mengobati sifat dengki yang telah bersemayan dalam hati:
“Syahdan jika datang dengki itu hendak mencacatkan atau mencederakan dia, tukarkan dan keluarkan dengan lidah membaiki dan memuji orang yang didengkinya itu. Dan jika datang dengki kita hendak takabur atasnya, tukarkan dengan kita rendahkan diri kepadanya. Dan jika datang dengki kita itu hendak menjatuhkan orang yang didengkikan itu, cari akal dan helah supaya bertambah-tambah baiknya, yakni baik kepada pangkat dan derajat. Dan jika datang dengki kita hendak menaham nikmat kepada orang yang didengkikan itu, gagahkan nafsu kita dengan menyampaikan nikmatnya. Dan jika datang dengki kita itu hendak mendengkikan dia dengan kejahatan, maka tukarkan dengan mendoakan dia dengan kebaikan.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 58).
Kutipan di atas jelas memperlihatkan kepiawaian Raja Ali Haji dalam merumuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar kendengkian kita itu tidak menimpa orang lain. Berdasarkan kutipan itu, kedengkian beserta implikasinya dapat dihindarkan dengan beberapa cara. Pertama, kalau ingin menghina atau mencederai seseorang, maka bicaralah yang baik-baik dan memberikan pujian kepadanya. Kedua, kalau ingin bersifat sombong kepada orang lain, maka bersikap rendah hati (tawaḍḍu’) kepadanya. Ketiga, kalau ingin menjatuhkan seseorang, maka pikirkan kebaikan dan kedudukannya. Keempat, kalau ingin menahan nikmat seseorang, maka kalahkan hawa nafsu serakah. Kelima, kalau ingin melakukan kejahatan terhadap seseorang, maka ganti dengan mendoakan kebaikan baginya.
Raja Ali Haji menambahkan bahwa usaha mengobati sifat dengki itu sangatlah sulit, dan bahkan mustahil tanpa memohon pertolongan Allah. Raja Ali Haji menyatakan karena “penyakit dengki itu penyakit pusaka daripada iblis laknatullah tatakala Allah Ta’ala mula-mula hendak menjadikan datuk kita nabi Allah Adam ‘alahi al-salam, seperti yang tersebut di dalam Qur’an al-‘Aẓim.” (Raja Ali Haji, Thamarāt al-Muhimmah, 58).
Prihal ini, al-Ghazali, guru intelektual dan mursyid spritual “tidak langsung” Raja Ali Haji, menyatakan bahwa “Tidak ada penyakit manusia yang tidak dapat disembuhkan, kecuali penyakit ḥasūd (iri hati) ini.” Guna mempertegas pernyataannya ini, al-Ghazali mengutip sebuah syair dari Imam al-Shafi‘i: “Kullu al-‘adāwatuh qad tarjī salāmatahā illa ‘adāwata min ‘ādāka ‘an ḥasad”. (Semua permusuhan bisa diselesaikan. Kecuali permusuhan orang yang menyimpan rasa rasa dengki). (Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011: 99). Bagaimana mungkin penyakit hasad (dengaki) akan disembuhkan kalau seseorang sudah terjangkit perasaan senang melihat orang lain susah, dan sebaliknya susah melihat orang lain senang. Dalam dua arah hatinya selalu tercengkrama kedengkian yang mengatarkan mereka dalam ketidakbahagiaan.
Wa Allāh a‘lam bi al-Ṣawāb,
Mā tawfīq wa al-Hidāyah illa bi Allāh.
Peneliti ISAIS (Institute for Southeast Asian Islamic Studies)
UIN Suska Riau.