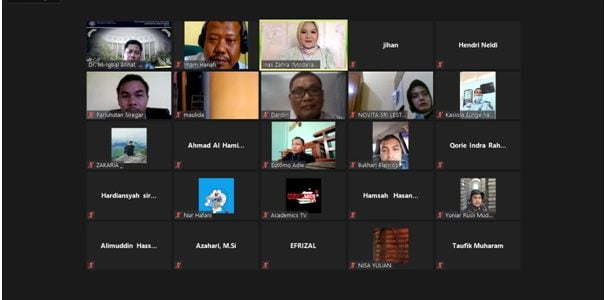Oleh Alimuddin Hassan Palawa
Sepeninggalan Raja Haji pada 1784, sebagai akibat kekalahan perang melawan Belanda, kerajaan Melayu-Riau dalam politik-militer bukanlah lagi suatu kerajaan berdaulat penuh. Dalam kenyataannya pemerintah Hindia Belanda kerapkali turut campur dan menentukan kebijakan dalam pemerintahan kerajaan Melayu Riau. Di akhir tahun 1784, misalnya, karena kebencian Belanda kepada orang-orang Bugis, pemerintah Belanda memberikan ultimatum kepada Sultan Mahmud –sebagai salah satu upaya adu domba– untuk mengusir orang Bugis dari kerajaan dan jabatan Yang Dipertuan Muda selama ini dijabat secara turun temurun di kalangan orang Bugis diperintahkan untuk dihapus.
Untuk itu, sultan sendiri harus menghadap kepada Jacob Van Braam di kapal komando Utrecht. Tentu saja ultimatum dan keinginan pemerintah Belanda ditolak sultan. Akibatnya terjadilah perang dengan Belanda dipimpin YDM V Raja Ali. Tentu saja perlawan ini dengan mudah dikalahkan Belanda. Akibatnya, YDM V Riau Raja Ali bin Kamboja beserta keluarganya meninggalkan Kerajaan Melayu Johor- Riau. (Lihat, Raja Ali Haji, Tuḥfat al-Nafīs, 213-222).
Konsekwensi logis dari kekalahan itu, Sultan Mahmud Syah terpaksa (tepatnya dipaksa) menandatangani perjanjian di bawah tekanan pemerintahan Belanda pada 10 November 1784.Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut antara lain dinyatakan bahwa seluruh pelabuhan dalam kerajaan Melayu Riau menjadi milik pemerintahan Hindia Belanda. Untuk itu, Hindia Belanda akan menempatkan tentaranya di kawasan kerajaan Melayu Riau dan pemegang monopoli perdagangan di kawasan Riau,danapabila sultan mangkat, penggantinya harus mendapat persetujuan dari pihak kolonial Hindia Belanda.
Kerajaan Melayu Riau semakin tidak berdaya menghadapi persekutuan pihak Belanda dan Inggris yang melahirkan Konvensi London 1814. Perjanjian kedua negara itu adalah bahwa Indonesia kembali diserahkan dan menjadi jajahan pemerintahan Hindia Belanda. Satu dekade berikutnya perjanjian itu diteguhkan dengan “The Anglo-Datch Treaty of London” atau lebih sering disebut “Traktat London 1824”. Sehingga kerajaan Melayu-Riau semula mencakup daerah Johor diserahkan kepada Inggris. (Rustam S. Abrur, Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah, 252-254). Kemudian, setelah perjanjian ini ditanda tangani, pemerintah memperbarui kontrak politik antara pemerintah Hindia-Belanda dengan Sultan Riau-Lingga yang semakin membatasi kekuasan dan wewenang sultan pada 29 Oktober 1830. (Hasan Junus, “Residen C.P.J. Elout: Arsitek Kontrak Politik 29 Oktober 1830” dalam Engku Putri Raja Hamidah Pemegang Regalia Kerajaan Riau (Pekanbaru: Unri Press, 2002), 196).
Pasca perjanjian-perjanjian disebut di atas, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa Kerajaan Melayu Riau-Lingga bukan lagi sebagai kerajaan yang berdaulat penuh. Meskipun dalam kondisi demikian, tidak berarti penguasa kerajaan Melayu Riau-Lingga tidak melakukan perlawanan dan mengupayakan kembalinya kedaulatan negerinya. Belakangan, pada 1903 raja terakhir kerajaan Melayu Riau, Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah melakukan perlawanan kultural yang sangat berani, yaitu dengan mengibarkan bendera kerajaan Belanda dipasang di bawah bendera Kerajaan Riau Lingga di depan istana. Residen Riau melaporkan persitiwa itu ke Batavia, dan Sultan Abdul Rahman mendapatkan peringatan keras dari Gubernur Jenderal Rooseboon di Batavia.
Pada kejadiaan lainnya, dalam menegakkan marwah dan kedaulatan kerajaan, Sultan Abdul Rahman menuntut agar Residen Riau tidak melakukan pengangkatan pejabat kerajaan sebab itu menjadi wewenang kerajaan.Sikap perlawanan sultan semakin jelas saat sultan enggan bekerja sama dan menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak baru) pada 1910. (Hasan Junus, Raja Ali Haji Budayawan, 225; Virginia Matheson, “Pulau Penyengat: Nineteenth Century Islamic Centre of Riau”, Archepel, 37(1989: 163).
Konsekwensinya, pada bulan Februari 1911 sultan dimakzulkan dari tahta kekuasaannya, dan putranya, Tengku Besar Umar dicoret namanya sebagai calon sultan. (Lihat, Rustam S. Abrur, Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah, 56). Surat abdikasi sultan dibacakan Residen Riau G. F. de Bruyn Kops(1911-1913) di markas gedung “Rushdiah Klab”, sebuah lembaga perkumpulan intelektual Melayu-Riau yang selalu kritis dan melakukan perlawanan secara moral terhadap kebijakan pemerintahan kolonial Belanda. (Lihat, Hasan Junus, “Upaya Menjual Riau”, 189).
Di kalangan pengurus Rusydiah Klab, setelah pemakzulan sultan, melakukan upaya diplomasi, misalnya tahun 1904-1905 kerajaan Melayu Riau mengutus Raja Ali Kelana untuk menemui Sultan Turki Utsmani di Istambul (Turki) guna meminta bantuan, tetapi upaya ini tidak berhasil. Selanjutnya, upaya diplomasi yang sama juga dilakukan pada 1905 oleh pihak kerajaan untuk menemui konsul Jepang di Singapura. Upaya diplomatis itu dilanjutkan lagi pada tahun 1912-1913 dengan mengutus Raja Khalid Hitam ke Tokyo untuk menemui Mahara Jepang guna meminta bantuan di dalam menghadapi penjajahan Belanda. Namun usaha-usaha diplomasi tersebut tidak berhasil di dalam menjalankan misinya. Malah Raja Khalid Hitam sendiri yang sedang menjalankan misinya di Jepang terbunuh pada 1914. Pembunuhan ini diduga kuat dilakukan oleh mata-mata Belanda. (Barbara W. Andaya, “From Rum to Tokyo: The Search for Anticolonial Allies by the Rules of Riau 1899-1914, dalam Indonesia, No. 24, (1977), 153-154).
Setelah keputusan pemakzulan Sultan Abdul Rahman tersebut, pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa seluruh tugas dan kewenangan sultan di kerajaan Melayu-Riau dan seluruh daerah kekuasaannya berada langsung di bawah kendali Residen Belanda. Seluruh rakyat Melayu Riau terpaksa/persisnya dipaksa untuk menaati segala peraturan kolonial Belanda. (Rustam S. Abrur, Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah, 326).Dalam kondisi seperti ini Sultan ‘Abd Rahman meninggalkan kerajaannya pergi ke Singapura, dan wafat dalam “pengasingannya” di sana pada 1930. Sebagian besar masyarakat mengikuti sultan meninggalkan Pulau Penyengat menuju Singapura. (Hasan Junus, “Upaya Menjual Riau”, 190; Virginia Matheson, “Pulau Penyengat: Nineteenth Century”, 163). Bahkan dapat dikatakan masyarakat “eksodus” meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju Singapura, Johor dan daerah-daerah sekitar lainnya.
Dari hasil penelitian Muhammad Afan, sebagaimana dikutip Hasan Junus, menyebutkan “… dari sekian ribu penduduk pulau kecil yang menjadi pusat pemerintahan di kerajaan itu hanya lebih kurang lima ratus jiwa saja yang tetap tinggal, karena sebagian besar penduduk pindah ke Johor dan Singapura.” Lihat, Hasan Junus, “Upaya Menjual Riau”, 190). Untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang “eksodus” meninggalkan Pulau Penyengat dapat dilihat dari data “perbandingan” berikut ini: (i) bahwa masyarakat yang tidak meninggalkan Pulau Penyengat haya tinggal 500 orang; (ii)_bahwa jumlah penduduk di pulau kecil ini pada akhir abad ke-19 diperkirakan mencapai sekitar 9.000 jiwa. Kedua data nyata menunjukkan bahwa Pulau Penyengat benar-banar ditinggal-pergi oleh penduduknya. (Virginia Matheson, “Pulau Penyengat: Nineteenth Century”, 162).
Raja Ali Kelana juga meninggalkan negeri kelahirnya dan menetap hingga wafatnya di Johor pada 1927. Raja Ali Kelana meninggalkan negerinya lantaran, menurutnya, telah “berubah kelakuannya” (diperintah Belanda). Raja Ali Kelana menyatakan prinsip ini, seperti katanya dalam Bughyāt al-‘Any fī Ḥurūf al-Ma‘āni: “Apabila negeri itu berubah kelakuannya maka tinggalkanlah dia!”Akhirnya, pemerintahan Belanda mengeluarkan keputusan penghapusan kerajaan Melayu Riau-Lingga dari “peta bumi” pada 11 Maret 1913. (Hasan Junus &UU. Hamidi, “Sumbangan dan Peranan Cendikiawan Riau”, 136; Rustam S. Abrur, Sejarah Perjuangan Raja Haji Fisabilillah, 326.
Dengan penghapusan kerajaan Melayu-Riau dari “peta bumi” pada sisi kekuasaan dan pemerintahan dapat dikatakan kerajaan Melayu Riau-Lingga ini tidak meninggalkan “bekas-bekas” kebesaran dan kejayaannya di masa silam.Apa penyebabnya Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan YDM Riau hampir tidak meninggalkan “bekas-bekas” kebesaran pada masa lalu. Menurut penelitian Matheson ini disebabkan orang-orang di Pulau Penyengat pada umumnya, dan raja-raja dan keluarga istana pada khususnya lebih memilih memusnahkan harta benda dan barang-barang yang ada dalam rumah mereka (melakukan semacam “bumi hangus” daripada (mereka khawatir kalau) Belanda akan menyita seluruh harta kekayaannya. (Lihat, Virginia Matheson, “Pulau Penyengat: Nineteenth Century”, 162).
Akan tetapi, dari sisi persuratan intelektual-keagamaan dan kebudayaan, kerajaan Melayu-Riau telah meninggalkan “jejak-jejak”kebesaran dan kejayaan masa lalunya –kendatipun belum/tidak sampai pada puncak kejayaan tertinggi– lewat generasi-generasi terpelajar yang menghasilkan “bertaburan” karya di Pulau Penyengat sepanjang menjelang paroh kedua abad ke-19 hingga awal abad ke-20. (Ong Hok Ham, “Pemikiran Tentang Sejarah Riau”, dalam Masyarakat Malayu Riau dan Kebudayaannya, 185).
Dengan situasi politik yang tidak menentu, maka ketika Indonesia memasuki era sastera modern yang ditandai dengan lahirnya Balai Pustaka pada dasawarsa kedua abad ke-20, Sapardi Djoko Damono menyebutkan, “tampaknya peran para sastrawan dari Riau tidak begitu menonjol”, untuk tidak mengatakan tenggelam sama sekali. (Lihat, Sapardi Djoko Damono, “Sastrawan Riau dan Sastra Indonesia Mutahir”, dalam Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan, ed. Heddy Shri Ahimsa-Putra (Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengambangan Budaya Melayu, 2007: 289-290).
Wa Allāh a‘lam bi al-Ṣawāb
Mā tawfīq wa al-Hidāyah illa bi Allāh
Alimuddin Hassan Palawa,
Direktur & Peneliti ISAIS (Institute for Southeast Asian Islamic Studies) UIN Suska Riau.